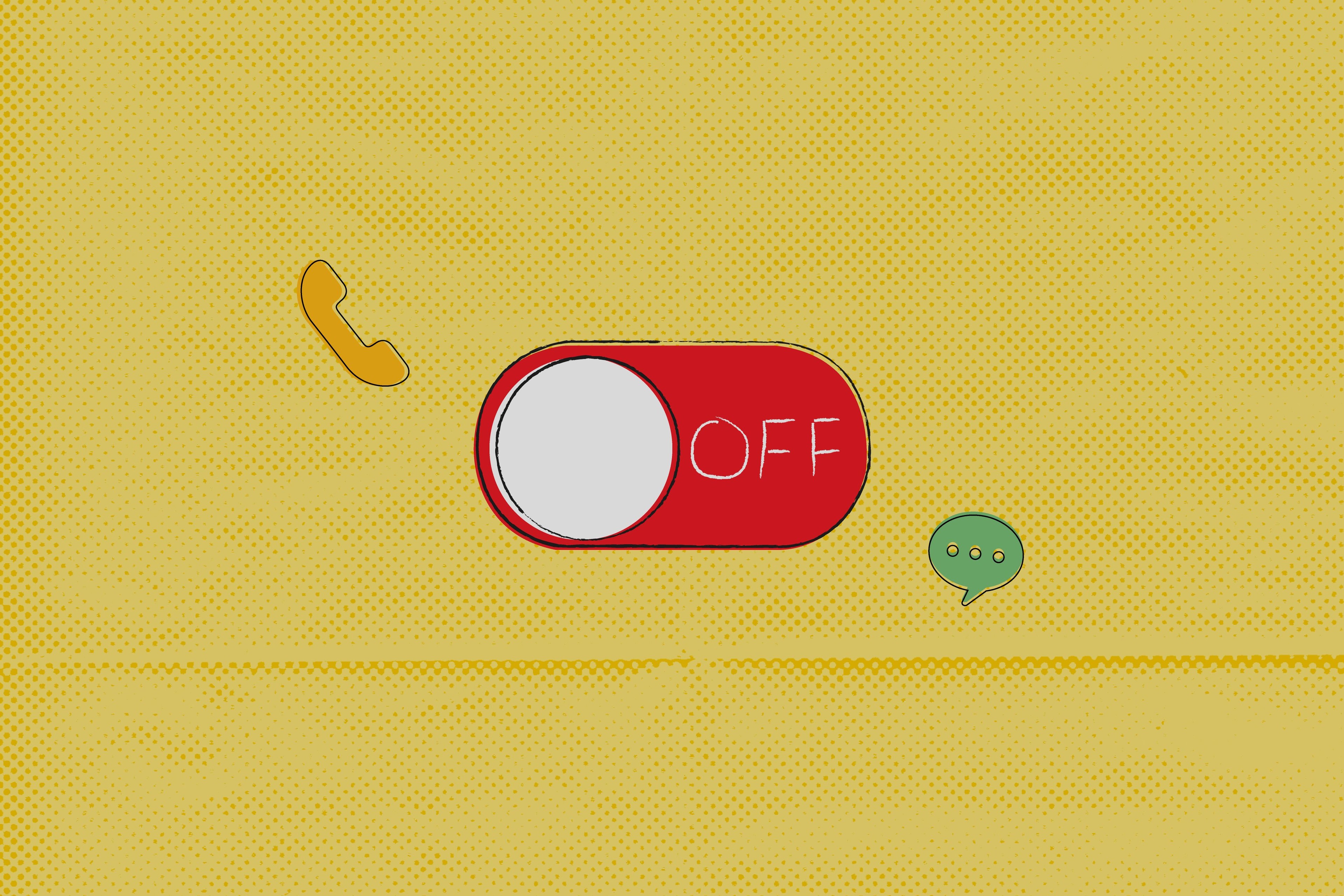
Insight Articles — Sep 09, 2022
Quiet Quitting: Loyal Tapi Secukupnya
3 mins read
Share this article
Quiet quitting secara literal berarti berhenti bekerja diam-diam. Pada praktiknya, gerakan ini sebenarnya dimaknai oleh Millennials dan Gen Z sebagai penerapan batasan yang wajar dalam pekerjaan. Quiet quitting seolah mendobrak hustle culture yang menurut generasi muda sedang berjalan ke arah yang nggak sehat. Sederhananya, quiet quitting berarti bekerja secukupnya.
Menurut mantan pekerja kreatif berinisial NP yang mengobrol dengan kami, dia mempraktikkan quiet quitting atas dasar keinginan menyeimbangkan work-life balance, menghindari burnout, dan agar ada waktu untuk kehidupan personal. NP merasa bekerja sewajarnya penting supaya kita masih bisa punya kehidupan di luar pekerjaan. Bahkan, dirinya memiliki tendensi untuk menghindari industri yang nggak bisa provide work-life balance.
Hal ini sepadan dengan penjelasan Editor LinkedIn News, Saundra Latham. Work-life balance sering jadi syarat dan prioritas Gen Z saat mencari pekerjaan. Saundra mengutip survei yang mengatakan Gen Z dan Millennials berusia muda menganggap pekerjaan sebatas sarana untuk mencapai tujuan hidup, bukannya menjadikan pekerjaan sebagai tujuan hidup sebenarnya (source: LinkedIn News).
Tapi, quiet quitting justru sering menjadi kontroversi di antara pekerja. Pekerja yang memprioritaskan work-life balance sering disebut nggak loyal terhadap perusahaan, apatis, atau bahkan anti mengembangkan diri. Hal ini karena pada praktek quiet quitting, para pekerja menolak tugas-tugas di luar job description atau kapasitas, pulang saat waktunya pulang, dan menolak obrolan pekerjaan di luar jam kerja (source: Tirto.id).
Tuntutan terhadap loyalitas ataupun hustle culture terutama banyak ditemukan di budaya bekerja Asia. New York Post menganggap quite quitting mirip dengan gerakan yang populer di China tahun lalu. Gerakan yang dikenal sebagai “lying flat” atau “tang ping” ini adalah pemberontakan para pekerja muda terhadap konsep jam kerja yang panjang dan sulit di China (source: nypost.com).
Gerakan quiet quitting seharusnya jadi wake up call untuk budaya bekerja di negara lain, berkaca pada “Karoshi” atau “death from overwork” yang sudah menjadi masalah menahun sejak 1970-an di Jepang. Hideyuki yang diwawancara oleh BBC bahkan mengatakan libur bekerja merupakan hal nggak umum di lingkungannya. “Saya tidak pernah memikirkan dampaknya bagi keluarga, kesehatan, dan kesejahteraan saya,” tambahnya (source: BBC.com).
Harvard Business Review saat mengadakan riset kepemimpinan selama beberapa dekade menemukan gerakan quiet quitting bukan disebabkan oleh para pekerja yang nggak mau bekerja lebih keras dan lebih kreatif, tapi ketidakmampuan para manajer dalam membangun hubungan yang baik dan menciptakan lingkungan yang nyaman untuk pekerja mereka. Sehingga lingkungan bekerja nggak dianggap sebagai lingkungan di mana para pekerja bisa memberikan usaha yang lebih ataupun berkembang. Para manajer lebih baik mengingat bahwa pekerja mereka cuma bisa didorong untuk memberi usaha yang lebih jika mereka merasa para pemimpin bisa memberikan timbal balik sepadan atau menunjukkan usaha yang sama (source: hbr.org).
Berdasarkan survei yang dilakukan tim Wonderwhy di Instagram Story ke 150 orang, 86% dari partisipan mengaku Millennials dan Gen Z. 89% diantara mereka setuju dan tertarik membuat boundary dengan quiet quitting. Bahkan, 75% dari mereka membenarkan hasil riset Harvard Business Review di atas yang menyatakan quiet quitting sering disebabkan oleh mismanagement dari manajer perusahaan.
Kesimpulannya, menjadi high performer memang bagus, tapi harus diingat kita juga bisa membatasi diri untuk menjadi high performer saat jam kerja saja. Lebih baik “work your wage” atau bekerja sewajarnya kamu dibayar. Saat mencari pekerjaan, pastikan lingkungan bekerja yang baru mendukung kebutuhanmu dan menyediakan working pace yang efisien. Jangan sampai mengorbankan kesehatan dan kehidupan pribadi kalau nggak dibarengi feedback yang sepadan dari perusahaan ya!
Reference:
- Gen Z embraces “quiet quitting”
- Quiet Quitting is About Bad Bosses, not Bad Employees
- The Surprising Origin of The “Quiet Quitting” Trend Sweeping Multiple Countries
- How the japanese are putting and end to extreme work weeks
- Quiet Quitting: Kami Tak Berhenti, Tapi Bekerja Secukupnya
Share this article
Related insight

